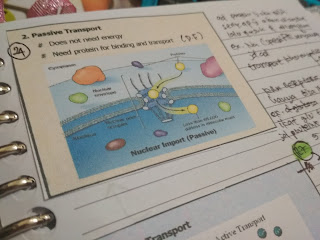Bismillah.
Kepergian
itu sulit. Tapi, kehilangan lebih sulit lagi. Mengapa orang-orang harus saling
meninggalkan? Jawabannya membawa saya ke sejumlah kesadaran dan perjuangan yang
terdalam. Pertanyaan itu juga membuat saya bertanya-tanya: setelah orang-orang
pergi, apakah mereka akan kembali? Setelah sesuatu yang kita cintai direnggut
dari kita, apakah itu akan kembali? Apakah kehilangan itu bersifat
permanen-atau sekedar sarana untuk tujuan yang lebih tinggi? Apakah kehilangan
adalah Akhir itu sendiri-ataukah kesembuhan sementara untuk penyakit hati kita?
Ada sesuatu
yang menakjubkan tentang kehidupan ini. Atribut duniawi yang sama yang
menyebabkan kita terluka juga memberi kita kelegaan: tak ada yang abadi. Apa artinya
itu? Artinya, mawar indah dalam jambangan akan layu besok. Itu berarti kemudaan
akan meninggalkan diri kita. Itu juga berarti kesedihan yang kita rasakan hari
ini akan berubah esok hari. Penderitaan kita akan lenyap. Tawa takkan bertahan
selamanya-tapi begitu pula dengan air mata. Kita berkata bahwa hidup ini tidak
sempurna. Hidup memang tidak sempurna. Hidup tidak sepenuhnya baik, tetapi juga
tidak sepenuhnya buruk.
Allah berfirman
dalam ayatnya yang sangat mendalam “Karena
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Al-Insyirah [94]:5).
Saya pikir saya tumbuh besar dengan keliru memaknai ayat ini. Awalnya saya
pikir artinya adalah: setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dengan kata
lain, tadinya saya pikir kehidupan terdiri atas masa-masa baik dan masa-masa
buruk. Setelah masa-masa buruk, akan datang masa-masa baik. Saya berpikir
seperti ini seolah-olah entah hidup sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Tapi
bukan itu yang dikatakan ayat tersebut. Ayatnya berkata bahwa bersama setiap kesulitan ada kemudahan.
Kemudahan hadir bersama kesulitan. Berarti
tidak ada apa pun di dunia ini yang sepenuhnya baik (atau buruk). Dalam setiap
situasi yang kita hadapi, senantiasa ada
sesuatu yang patut kita syukuri. Bersama setiap kesulitan, Allah memberi kita
kekuatan dan kesabaran untuk menanggungnya.
Jika mengkaji
masa-masa sulit dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa masa-masa itu diisi
denga banyak kebaikan. Pertanyaannya adalah: mana yang akan kita pilih untuk
kita fokuskan? Saya rasa kita telah terjerumus ke dalam perangkap yang berakar
dari keyakinan keliru bahwa hidup bisa jadi sempurna-sempurna baiknya atau
sempurna buruknya. Meskipun itu bukan sifat dari dunia (kehidupan ini). Itu adalah sifat dari akhirat. Di akhirat
bisa dicapai berbagai tingkat kesempurnaan. Jannah
(surga) itu sempurna baiknya. Tak ada keburukan di dalamnya. Dan jahannam (neraka-semoga Allah melindungi
kita) itu sempurna buruknya. Tak ada kebaikan di dalamnya.
Dengan
tidak sepenuhnya memahami realitas ini, saya sendiri akan dikuasai oleh keadaan
fana kehidupan saya (entah itu baik atau buruk). Saya mengalami setiap situasi
dalam intensitasnya yang penuh-----seolah-olah itu adalah akhir atau justru
takkan pernah berakhir. Apa yang saya rasakan pada saat itu mengubah seluruh
dunia dan segala isinya. Jika saya merasa senang pada saat itu, masa lalu
maupun masa kini, dekat dan jauh, seluruh semesta akan terasa baik pula pada
saat itu. Seolah-olah kesempurnaan bisa diraih disini. Hal yang sama pun
berlaku pada hal yang buruk. Kondisi negatif menguasai segalanya. Rasanya seluruh
dunia, masa lalu dan masa kini, seluruh semesta akan terasa buruk pada saat
itu. Karena hal itu menjadi seluruh semesta saya, saya tidak bisa melihat
apapun yang ada diluarnya. Tak ada apa pun yang eksis pada saat itu. Bila anda
memperlakukan saya dengan buruk pada hari ini, itu karena Anda tidak lagi
peduli kepada saya---bukan karena ini adalah salah satu dari momen tak
terhingga banyaknya yang kebetulan terwarnai seperti itu, atau bukan karena
Anda dan saya dan kehidupan ini tidaklah sempurna. Apa yang saya alami atau
saya rasakan pada saat itu menggantikan konteks, karena itu menggantikan
seluruh visi saya tentang dunia.
Menurut
saya, sehubungan dengan pembawaan yang eksperiensif, sebagian dari kita mungkin
sangat rentan dengan hal itu. itulah sebabnya kita menjadi mangsa dari fenomena
“Aku belum pernah melihat sedikit pun
kebaikan darimu”. Sebagaimana yang dirujuk oleh Rasulullah dalam hadistnya.
Mungkin sebagian dari kita berkata atau merasa seperti ini karena pada saat itu
kita memang benar-benar tidak melihat kebaikan karena perasaan kita pada detik
itu menggantikan, menentukan, dan menjadi segalanya. Masa lalu dan masa kini
tergulung menjadi satu dalam momen eksperiensif tersebut.
Namun,
kesadaran sejati bahwa tidak ada yang utuh dalam kehidupan ini mengubah
pengalaman kita soal itu. Sekonyong-konyong, kita tidak lagi dikuasai oleh
momen tersebut. Dengan memahami bahwa tak ada yang tidak terbatas disini, bahwa
tidak ada sesuatu pun disini yang bersifat kamil
(sempurna, lengkap), Allah memungkinkan kita untuk melangkah keluar dari
momen dan melihat mereka sebagaimana apa adanya; bukan semesta, bukan realitas,
masa lalu dan masa kini, hanya suatu momen---satu momen tunggal dari
serangkaian momen tak terhingga yang juga akan segera berlalu.
Ketika
saya menangis, kehilangan, atau terluka, selama saya masih hidup, tak ada yang
namanya penghabisan. Selama masih ada hari esok, masih ada momen selanjutnya,
senantiasa ada harapan, ada perubahan, dan ada penebusan. Apa yang telah hilang
takkan hilang selamanya.
 |
| sourch of pict |
Jika,
dalam menjawab pertanyaan apakah yang hilang akan kembali, saya mempelajari contoh paling indah.
Apakah Yusuf kembali kepada ayahnya? Apakah Musa kembali kepada ibunya? Apakah
Hajar kembali kepada Ibrahim? Apakah kesehatan, kekayaan, dan anak-anak kembali
kepada Ayub? Dari cerita ini kita mendapatkan pembelajaran yang kuat dan indah: apa yang diambil oleh Allah
tidak akan pernah hilang. Bahkan, hanya yang ada di sisi Allah yang tersisa. Segala
hal lainnya lenyap. Allah berfirman: “Apa
yang disisimu akan lenyap, dan apa yang ada disisi Allah adalah kekal. Dan
sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan
pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl [16]:96).
Semua
yang ada disisi Allah, tidak pernah hilang. Bahkan Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan
sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik
bagimu” (HR. Ahmad). Bukankah Allah mengambil suami Ummu Salamah hanya
untuk menggantikannya dengan Rasulullah?
Terkadang
Allah mengambil agar dapat menganugerahi. Tapi, penting untuk dipahami bahwa
anugerah Allah tidak selalu berupa apa yang kita pikir kita inginkan. Allah
mengetahui apa yang terbaik. Allah berfirman, : “.... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah [2]: 216).
Tapi
jika sesuatu akan dikembalikan dalam satu bentuk atau justru yang lainnya,
untuk apa diambil sama sekali? Subhanallah.. Justru dalam proses “kehilangan”
itulah kita mendapat anugerah.
Allah
menghadiahi kita anugerah, tapi kemudian kita seringkali bergantung pada anugerah-anugerah itu,
alih-alih kepada-Nya. Ketika Allah menganugerahi kita uang, kita bergantung
pada uang itu—bukan kepada-Nya. Ketika Ia menganugerahi kita seseorang, kita
bergantung kepada orang itu—bukan kepada-Nya. Ketika Ia menganugerahi kita
status, atau kekuasaan, kita bergantung pada hal itu, dan perhatian kita
menjadi terganggu olehnya. Ketika Allah menganugerahi kita kesehatan, kita
menjadi terperdaya. Kita menyangka kita tidak akan mati.
Allah
menghadiahi kita anugerah-Nya, tapi kemudian kita malah mencintai
anugerah-anugerah itu, padahal seharusnya kita hanya mencintai-Nya. Kita
menerima anugerah-anugerah tersebut dan menyuntikkannya ke dalam hati kita,
sampai mereka mengambil alih. Segera saja, kita tak bisa hidup tanpa mereka. Setiap
waktu terjaga kita habiskan untuk menekuri anugerah-anugerah itu, mematuhi dan
menyembah mereka. Pikiran dan hati kita yang diciptakan oleh Allah, untuk
Allah, menjadi milik seseorang atau sesuatu yang lain. Ketika ketakutan itu
datang, rasa takut akan kehilangan mulai melumpuhkan kita. Anugerah-anugerah
tersebut—yang seharusnya tetap berada ditangan kita—mulai mengambil alih kita,
sehingga rasa takut akan kehilangan hal itu menguasai kita. Segera saja, apa
yang tadinya merupakan anugerah berubah menjadi senjata penyiksaan dan penjara
buatan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa terbebas dari hal ini? Terkadang,
dalam belas kasih-Nya yang tiada batas, Allah membebaskan kita... dengan
mengambilnya.
Karena
hal itu diambil, kita berpaling kepada Allah sepenuh hati. Dalam keputusasaan
dan kebutuhan itu, kita meminta, kita memohon, kita berdoa. Melalui kehilangan,
kita mencapai tingkat ketulusan dan kerendahan hati dan ketergantungan
kepada-Nya yang jika sebaliknya tidak akan kita capai—seandainya anugerah itu
tidak diambil dari kita. Melalui kehilangan, hati kita berpaling sepenuhnya
kepada Allah.
Apa yang
terjadi ketika Anda pertama kali memberi anak Anda mainan atau video game baru yang selalu dia
inginkan? Dia dikuasai oleh hal itu. Segera saja, dia tak mau melakukan apapun
lagi. Tidak melihat apapun lagi. Dia tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya atau
bahkan makan. Dia terhipnotis untuk merugikan dirinya sendiri. Jadi, apa yang
Anda lakukan sebagai orang tua yang penuh kasih? Apakah Anda biarkan dia untuk
tenggelam dalam adiksi serta kehilangan fokus dan keseimbangan sama sekali?
Tidak.
Anda
mengambil mainan itu.
Kemudian,
setelah anak Anda memperoleh kembali fokus prioritasnya, memperoleh kembali
kewarasan dan keseimbangannya, begitu segalanya diletakkan di tempat yang tepat
di hati dan pikiran dan hidupnya, apa yang terjadi? Anda mengembalikan mainan
itu. Atau, barangkali Anda memberi sesuatu yang lebih baik. Tapi kali ini,
hadiah itu tak lagi berada di hatinya, melainkan berada di tempat yang tepat.
Yaitu ditangannya.
Namun,
dalam proses pengambilan itu, hal yang paling penting terjadi. Kehilangan dan
mendapatkan kembali anugerah itu tidaklah penting. Menghapuskan kelalaian,
fokus dan kertergantungan Anda pada hal lain selain pada-Nya, dan
menggantikannya dengan mengingat, bergantung, dan fokus hanya kepada Allah,
itulah anugerah yang sebenarnya, Allah menangguhkan anugerah-Nya.
Sehingga,
kadang-kadang, “sesuatu yang lebih baik” merupakan anugerah terbesar: kedekatan
kepada-Nya. Allah mengambil anak perempuan Malik bin Dinar untuk
menyelamatkannya. Allah mengambil anak perempuannya, tapi menggantinya dengan
perlindungan dari api neraka dan keselamatan dari kehidupan penuh dosa yang
menyakitkan dan berjarak dari-Nya. Melalui kehilangan sang putri, Malik bin
Dinar diberkati dengan kehidupan yang dihabiskannya untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Bahkan putrinya yang telah diambil akan tetap bersama Malik bin
Dinar selamanya di Jannah.
Ibnu
Qayyim (semoga Allah meridhoinya) membahas tentang fenomena ini dalam bukunya, Madarij Al-Salikin. Dia berkata, “Ketetapan
Tuhan terkait dengan orang-orang mukmin selalu merupakan karunia, bahkan jika
itu berupa penangguhan (sesuatu yang diinginkan); dan merupakan berkah, bahkan
jika itu kelihatannya merupakan cobaan dan penderitaan yang menimpa dirinya;
dan merupakan obat, meskipun kelihatannya sebagai penyakit!”
Jadi,
untuk pertanyaan “Begitu sesuatu hilang, apakah ia akan kembali?” jawabannya
adalah ya. Ia akan kembali. Terkadang disini, terkadang disana, terkadang
berupa sesuatu yang berbeda, tapi lebih baik. Namun, anugerah terbesar terletak
di balik pengambilan dan pengembalian itu. Allah memberi tahu kita dalam
firman-Nya, “Katakanlah: ‘Dengan karunia
Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan
rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Yunus [10]:58) :)
:) :)
Disadur
dari
Kepingan hikmah dalam buku
karya: Yasmin Mogahed, berjudul “Reclaim
your heart”, yang diterjemahkan oleh Nadya Andwiani.